Perlukah Kita "Memperbaiki" Orang Tua?
03:03 |
| via health.harvard.edu |
Dalam hidup, kita belajar setiap hari dan berkembang lewat berbagai permasalahan yang kita hadapi. Seiring waktu, kita menjadi berpengetahuan, berpengalaman, dan dewasa. Seringkali, pengetahuan dan kebijaksanaan kita melesat melampaui orang tua, dan kita seringkali jadi merasa kesal dengan kekeraskepalaan orang tua.
Ada saatnya kita berselisih paham karena perbedaan cara memandang masalah. Masing-masing merasa benar dengan pendapatnya masing-masing; si anak merasa ada yang salah dari cara orang tuanya berpikir dan ingin memperbaikinya, sementara si orang tua merasa tidak ada yang perlu diperbaiki. Mungkin secara bawah sadar ada rasa malu atau gengsi karena si anak telah menjadi orang yang lebih berpengetahuan, atau memang merasa lebih tua jadi lebih berpengalaman, dan karenanya lebih berpengetahuan.
Nah, pertanyaannya: perlukah kita "memperbaiki" orang tua?
Sebagai anak, saya mencintai ibu saya (ayah saya sudah almarhum) dan ingin segala yang terbaik untuk beliau. Saya mengagumi ibu saya dengan kecantikanNya, keanggunanNya, caraNya mendidik anak-anakNya sehingga bisa menjadi dewasa hingga sekarang. Tapi entah kenapa, di satu titik ibu saya seperti "berhenti" berkembang. Ia seperti melambat. Entah daya tangkapNya yang melambat, atau saya telah berkembang sebegitu pesat melampauinya. Meski saya setuju dengan sebagian besar cara berpikirNya, namun saya tahu, dengan tambahan satu atau dua hal lagi pemikiranNya bisa jadi "sempurna"--atau setidaknya jadi sama persis dengan pemikiran saya.
Tapi rupanya tidak semudah itu menyampaikan satu/dua hal tersebut. Saya perlu mengalami berbagai adu mulut, caci-maki, dan tangisan selama bertahun-tahun sampai saat ini saya tersadar dan menulis artikel ini. "Sebagai orang tua pasti malu kalau ditentang dan disalah-salahin terus," demikian adik saya berujar. Ya, mungkin hal ini yang tidak pernah saya sadari sebelumnya karena saya bukan seorang orang tua. Meski saya tidak punya niatan apapun untuk menentang atau menyalahkan, tapi lebih kepada berbagi ilmu yang saya miliki dan tanpa sadar berusaha "memperbaiki", rupanya ini pun masih merupakan produk ego saya yang ingin menjadikan orang tua saya lebih sempurna lagi menurut pemikiran saya.
Baru-baru ini saya meluncurkan video renungan tentang arti "Sempurna". Meski sangat halus, sepertinya saya pun punya standard kesempurnaan tersendiri. Mungkin saya bisa bersikap tidak peduli terhadap perkembangan spiritualitas orang lain, tetapi karena ini adalah ibu saya sendiri, saya punya kecenderungan yang agresif untuk mempromosikan cara berspiritual yang telah saya tempuh supaya juga bisa diikuti oleh ibu saya. Banyak orang lain terbukti bisa menerima dan berhasil mengaplikasikan cara yang saya pelajari ini, tapi mengapa ibu saya tidak bisa?
Sebagai anak, tentu saya ingin ibu saya mengalami pencerahan dan kedamaian batin seperti yang saya alami. Ketika ibu saya datang pada saya curhat tentang perdebatan atau pengalaman buruk yang terjadi, biasanya kami bisa berdiskusi lewat metode spiritual untuk saling mengambil pelajaran dari setiap kasus. Tetapi beberapa bulan terakhir, saya ingin berbagi sudut pandang baru dan cara saya mengatasi masalah-masalah tanpa masalah--yaitu dengan kesadaran. Kalau saya bisa--dan orang lain juga bisa, kenapa ibu saya tidak bisa?
Tapi ibu saya tidak mau. Ia mau menempuh jalanNya sendiri--yang menurut saya "ini lho, saya sudah temukan short-cut dan formulanya, jadi tinggal ikuti saja" tetapi menurutnya ada cara lain yang bisa Ia tempuh menuju ke sana. Biasanya saya tidak mendebatNya, tapi setiap kali ada perbincangan tentang spiritualitas ini obrolan kami berakhir dengan teriakan-teriakan satu pihak.
Malam ini, lewat obrolan singkat lewat tengah malam dengan adik saya, saya disadarkan bahwa selama ini saya memperlakukan ibu saya sebagai kawan (diskusi spiritual), bukan sebagai ibu. Kadang kita merasa terlalu sayang dan ingin berbagi segala hal yang baik menurut kita, namun tidak diterima dengan baik oleh orang tersebut karena cawannya telah penuh. Dan jika sebuah cawan sudah penuh, ia tidak punya ruang kosong untuk menerima sesuatu yang baru. Kalaupun terisi setengah, yang baru akan tercampur dengan pengetahuan yang lama, sehingga muncul sebuah pemahaman/pengetahuan yang baru lagi--yang malah jadi berbeda dengan "ilmu" yang kita isikan tadi.
Saya belajar dari pengalaman sejarah. Ketika tante-tante saya berusaha "memperbaiki" nenek saya dengan masing-masing pemahaman mereka, mereka tidak membuat nenek saya bahagia--beliau malah menderita dalam keheningan masa tuanya. Anak-anaknya sibuk memaksakan pemikiran mereka--yang mungkin memang lebih benar--tetapi tidak memperhatikan kebahagiaan dan menghargai pilihan nenek.
Saya rasa, saya tidak mau mengulangi itu untuk ibu saya. Jika Ia bahagia dengan pemikiranNya, saya rasa saya bisa belajar untuk membiarkan saja tanpa perlu "memperbaiki", dan memberiNya kebahagiaan daripada perasaan ditentang dan disalah-salahkan. Lucu, karena saya merasa ibu saya masih muda untuk merasa tua; dandanan dan gaya hidupnya sama sekali tidak menyiratkan penuaan. Tetapi perlu penyadaran dari pihak saya kalau 62 bukanlah usia muda. Dan ibu saya berhak hidup damai dengan apa pun pilihanNya.
Saya rasa memang pelajaran hidup paling berat kita pelajari lewat orang terkasih kita. Dan dalam kasus ini, saya dan ibu saya. Tadi saya belajar untuk menerima, dan "menahan diri" untuk tidak mendebat. Tetapi mulai sekarang, saya belajar untuk menerima saja apa adanya, tidak berusaha memperbaiki, dan sebaliknya, memberi ibu saya kedamaian dan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Memilih kasih daripada memenangkan ego. Sungguh harga yang mahal untuk pelajaran ini, tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk mempraktikkannya. Saya harap perenungan ini bisa menginspirasi Anda, apa pun bentuk permasalahan Anda.
Rahayu,
_/|\_








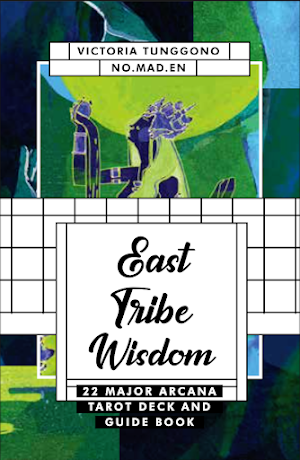









0 comments
Terima kasih sudah memberi komentar. Mohon kesabarannya menunggu saya baca dan balas komennya ya. Rahayu.