Renungan: Guru Spiritual
12:53[catatan: artikel ini mungkin lebih nyaman dibaca di layar ponsel ketimbang desktop / laptop]
Enam tahun terakhir, saya bertemu banyak sekali pejalan spiritual. Karena saya mulai tertarik dengan "dunia" ini, sepertinya Semesta pun membukakan pintu yang isinya penuh dengan orang-orang sefrekuensi. Yang tidak selaras perlahan tersisihkan, dan semakin ke sini yang saya temui semakin banyak yang satu tujuan. Sebenarnya ini menyenangkan--bertumbuh dalam pengetahuan & perjalanan spiritual bersama, walau sebagian besar baru saya kenal 1-3 tahun terakhir.
Dalam perjalanan ini saya juga banyak bertemu dengan guru spiritual, istilah yang kita sematkan pada orang-orang berpengetahuan dan berpengalaman spiritual luas yang membagikan ilmunya pada para pemula seperti saya. Guru ini bisa siapa saja sebetulnya, selama kita bisa belajar sesuatu darinya. Tapi saya menitik beratkan objek artikel ini pada orang-orang yang mendedikasikan dirinya di dunia spiritual dan mengajar orang banyak.
Sejak pertama kali nyemplung di dunia ini, hidup saya bisa dibilang sangat absurd. Dalam bahasa Indonesia, istilah absurd merujuk pada lucu, konyol, mustahil, menggelikan, tak masuk akal. Bisa dibilang, begitulah hidup saya sekarang (salah satunya bisa dibaca di artikel ini, atau ini). Tapi kita tidak membahas itu sekarang. Yang saya mau ceritakan adalah pengalaman bertemu orang-orang absurd yang menjadi guru saya. Sifat mereka macam-macam, dan caranya pun beragam. Tentu tidak ada orang yang punya pengalaman persis sama, dan itulah mengapa saya punya banyak guru dalam belajar spiritual.
Berguru Dari Buku
Sebelum sepenuhnya menjalani hidup spiritual, saya belajar banyak dari buku. Awalnya, buku Embraced By The Light oleh Betty J. Eadie. Lalu saya bertemu Paulo Coelho dengan The Alchemist sampai Aleph-nya, yang sangat memengaruhi perspektif saya memandang hidup. Buku-buku berikutnya menjadi pelengkap bagi saya, sampai saya menemukan buku-buku mas Herwiratno (pernah diulas di sini) dan Suwung karya Setyo Hajar Dewantoro.
Yang satu, saya ketemu orangnya dulu baru baca bukunya. Yang satu lagi baca bukunya dulu baru ketemu orangnya. Tapi saya belajar banyak dari keduanya, di samping guru-guru lain yang tidak menulis buku (bisa baca rangkumannya di sini). Pengalaman saya bertemu guru-guru ini semuanya menarik dan--sekali lagi--absurd. Tapi saya langsung ke intinya saja: saya tidak pernah mengabdi.
Dalam buku / film silat atau kung fu (seperti karya Kho Ping Hoo) kita melihat betapa satu murid bisa sebegitu mengabdinya pada seorang guru seumur hidup. Entah saya berpikiran terlalu modern atau Barat, saya tidak melakukan itu. Mengabdi, mungkin artinya mendedikasikan diri untuk (selalu) ikut kelas-kelas kajian, mengagung-agungkan sosok sang guru, dst. Tapi jalan hidup saya tidak mengajarkan saya untuk jadi seperti itu. Sejak awal saya belajar dari sosok-sosok ini dalam wacana / diskusi, obrolan ringan berbobot, dan biasanya memang one-on-one alias tidak dalam kelas.
 |
| via themichaelteachings |
Berguru Di Kelas
Belakangan saya baru tahu kalau ada kelas-kelas spiritual, karena sepanjang 32 tahun usia saya tidak pernah ikut kelas spiritual maupun belajar meditasi. Baru dua tahun terakhir saya belajar meditasi (yang awalnya juga dipaksa oleh teman), dan beberapa bulan terakhir mulai ikut hadir dalam kelas spiritual. Oke, ini pengalaman baru. Tapi pola pikir saya yang sudah terbentuk sejak dulu menjaga saya dari sikap mengagungkan / mengkultuskan orang, sesakti / sesuci apapun beliau [tambahan: bahkan sekalipun beliau mengaku titisan dewa tertentu dan mengatakan bahwa kita adalah dewi pasangannya--terlepas dari valid / tidaknya pernyataan itu, wallahu a'lam--karena di kehidupan yang sekarang hari ini kita semua punya raga dan roh dan ego yang berbeda jadi jelas kita manusia bukan dewa; jadi tak usah terjebak dalam romantisme masa lalu karena itu semua sudah berlalu.]
Saya rasa ini adalah tips pertama yang saya mau bagikan di sini, karena banyak teman yang saya lihat terjebak dalam sikap ini. Mengagungkan / mengkultuskan orang sama saja menganggap orang lain sebagai dewa / Tuhan. Tapi semua guru di dunia, termasuk pemuka / pemimpin agama pun, adalah manusia belaka. Mereka masih hidup, berbentuk daging (keduniawian) dan terikat hukum fana yaitu punya kebutuhan ragawi. Maka dalam pikiran saya pun tidak ada seorang manusia pun yang suci. Hati bisa murni, tapi selama masih manusia, tidak satu pun dari kita terbebas dari 'dosa'--baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan.
Hal kedua yang saya mau bagikan adalah, jangan percaya pada guru manapun. Sebaik atau benar apapun perkataan mereka, yang mereka sampaikan pada kita adalah hal-hal berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Jadi penting dalam hal berguru ini untuk punya sebuah keterampilan yang bernama 'memaknai'.
[Dalam sebuah acara peluncuran buku tempo hari saya belajar dari Dr. Felicia Nuradi Utorodewo, S.S. bahwa proses belajar adalah membaca / mendengar > memahami > memaknai > bisa menceritakan kembali dengan versi sendiri; artinya kita tak saja paham pelajarannya tapi bisa mengambil makna / intisarinya, sehingga merasuk hingga ke jiwa, bukan hanya sekadar hafalan semata.]
Fungsi seorang guru tak lebih sebagai 'pembuka pintu'. Mereka membagikan cerita pengalaman dan ilmu pengetahuan mereka hanya sebatas untuk menginspirasi; mengetok jiwa-jiwa yang masih tertidur. Mereka menjawab panggilan untuk membantu jiwa kita bangkit, tetapi biasanya tak akan ikut bertualang bersama. Mereka membukakan pintu, tapi tidak menggandeng tangan kita.
Seringkali tangan saya malah digandeng oleh rekan seperjalanan yang sama-sama sedang belajar; dan memiliki guru serta rekan sejawat merupakan dua hal yang sama-sama penting dalam perjalanan spiritual ini. Jadi jangan pernah menggantungkan harapan atau tujuan pada guru spiritual. Mereka menjalankan tugas mereka--dan kita berterima kasih untuk itu--tapi kebanyakan guru yang saya kenal malah menendang jauh murid-muridnya untuk menjalani laku spiritual untuk berkembang sendiri setelah membekali dengan ilmu yang cukup.
Karena memang itulah inti dari perjalanan spiritual: mengalami dan belajar sendiri dalam laku dan pemahaman diri, karena setiap manusia diciptakan dengan latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan berbeda; jatah berbeda; tugas berbeda. Maka pelajaran dan pemahaman masing-masing pun akan berbeda. Dalam membaca sebuah buku / menonton sebuah film saja setiap orang akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, sesuai dengan cara berpikir, selera, dan pengalaman masing-masing. Jadi memang tidak ada yang baku dalam dunia spiritual ini: semua fluid / cair / mudah berubah, seperti halnya air yang mengikuti bentuk wadahnya.
Berguru Pada Diri
Pada akhirnya, kita akan menemukan guru sejati yang sangat bisa kita percaya: diri sendiri. Ada suara batin / nurani / kesadaran murni / higher consciousness / percikan Tuhan / Roh(ul) Kudus / Sang Atman / Dewa Ruci di dalam diri setiap manusia yang seringkali terblokir oleh logika dan energi negatif. Inilah yang disebut sebagai 'Guru Sejati yang bertahta di dalam hati', karena kesadaran ini tahu apa yang terbaik untuk diri masing-masing. Itulah sebabnya RMP Sosro Kartono konon berkata:
Murid gurune pribadi, guru muride pribadi.
Pamulangane, sengsarane sesami.
Ganjarane, ayu lan arume sesami.
[Seorang murid adalah guru bagi dirinya sendiri. Seorang guru adalah murid dirinya sendiri (dalam diri setiap manusia ada sifat pembelajar / ingin tahu dan sifat mengajari / sudah paham). Tempat belajarnya adalah penderitaan sesama (belajar dari memperhatikan kejadian sekitar & pengalaman). Hasilnya adalah keindahan dan keharuman sesama (hasil pembelajaran & pengaplikasiannya bisa membantu sesama dalam bertumbuh bersama.]
Hal berikutnya yang saya mau bagi berdasarkan pengalaman saya, adalah proses penyaringan. Penting bagi setiap pembelajar untuk punya filter yang berfungsi secara objektif dan jernih. Artinya, dalam menyaring informasi apapun kita harus senantiasa berada di zona netral, tidak ada kepentingan, dan tidak subjektif. Dan filter ini berfungsi untuk memilah mana informasi yang bisa kita terima dan serap, mana yang hanya ditampung sebagai pengetahuan (asal tau aja).
Saya punya beberapa fungsi filter yang saya aktifkan. Pertama, yang tertulis (buku maupun chatting). Dalam membaca setiap pesan saya tak sengaja mengaktifkan filter ini dan mendeteksi adanya selipan ego / kepentingan pribadi sang penulis. Ada seorang guru yang setiap tulisan / kata bijaknya selalu menyelipkan pencitraan diri (menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya guru yang telah mencapai kesempurnaan jiwa), pembenaran diri (berdalih bahwa yang ia lakukan hanyalah mengikuti alur Semesta), dan kadang menyertakan ancaman (jika tidak mengikuti dia akan celaka; kebenaran hanya terjadi jika kita menuruti cara-caranya). Ini semua adalah produk ego.
Sangat disayangkan jika seorang guru spiritual dengan banyak murid harus menggiring para pejalan yang haus pengetahuan kembali ke pola pikir agamais (dalam bentuk organisasi / mendirikan jenis kultus baru dengan dia sebagai nabinya) sementara pembelajaran spiritual adalah hal yang justru mengarah sebaliknya: menuju pada kemandirian diri dan lepas dari segala bentuk dualitas [benar-salah, suci-dosa, baik-buruk, dst] yang sangat duniawi. Prinsip spiritual adalah 2-1-0. Lepas dari dualitas kita menyatu jiwa-raga-hati-pikiran, lalu terakhir kita suwung / kosong.
Filter kedua diaktifkan saat bertatapan muka. Ketika bertemu dengan seseorang, tentu kita punya insting yang langsung mengkategorikan orang itu ke dalam bilik yang kita punya. Ada orang yang langsung bisa kita percaya karena auranya menenangkan sekalipun cara bicaranya blak-blakan / tegas, dan ada yang walau wajahnya selalu tersenyum dan tutur katanya halus tapi ada rasa janggal yang membuat kita jengah berada dekat-dekat. Bagaimanapun bentuk orang itu, asahlah rasa untuk mendeteksi isinya (jiwanya). Hal ini penting untuk mencegah diri kita terjerumus menuju ketersesatan.
Lalu, filter ketiga adalah memperhatikan tindakan / tingkah laku. Kita memang tidak bisa menilai banyak ketika orang itu sedang tampil karena tentu ia akan menampilkan sisi terbaiknya, tapi jiwa / karakter seseorang akan terlihat dari apa yang dilakukan di luar sorotan. Seperti bagaimana ia memperlakukan yang strata sosialnya di bawah dirinya, memperlakukan pasangan / keluarganya, dan terhadap orang-orang yang melukai (harga) dirinya. Jika ia tidak bisa berbesar hati, jelas bukan sosok yang patut dicontoh.
Pada intinya, filter ini tak lebih dari mengasah rasa. Mendengarkan apa yang ditangkap oleh Sang Atman dalam diri kita, yang membimbing kita dalam jalan kebenaran dan menjauhkan kita dari segala ilusi dan petaka. Jangan sampai status dan penampilan menipu otak kita dan membuat kita mengagungkan seseorang hanya karena kita merasa ia berjasa dalam memberi kita sebuah ilmu. Mengajar adalah kewajibannya, jadi tidak usah terjebak romantisme guru-murid di sini. Dan ingat hanya ada satu sosok yang pantas kita agungkan: Sang Atman di dalam diri; jiwa kita sendiri.
Seorang guru yang saya temui berpikir kalau dirinya bertanggung jawab atas perkembangan spiritual murid-muridnya. Ia memposisikan diri sebagai guru yang harus menuliskan raport hasil pembelajaran sang murid. Padahal kita semua tahu, hak menilai adalah milik Tuhan, bukan milik guru. Hal ini adalah dalih pembenaran untuk sejumlah murid yang ia perhatikan secara khusus. Tidak mungkin ada orang yang bisa sebegitu bertanggung jawabnya atas jiwa ratusan bahkan ribuan orang--ini sebuah pencitraan saja kok. Sebagian besar pasti tak ia pedulikan, hanya sebagian yang menonjol yang ia perhatikan.
Bahkan dari apa yang saya pelajari dari guru lain malahan menjadi antitesis perilaku ini: tidak ada orang yang boleh merasa bertanggung jawab atas jiwa orang lain; yang perlu ia pertanggung jawabkan adalah jiwanya sendiri (baca di sini). Perlu dicurigai jika seorang guru merasa punya tanggung jawab berlebihan seperti ini. Apa motif di balik rasa tanggung jawab ini?
Latihan mengenali rasa ini bisa jadi sangat menarik ketika kita bertemu dengan orang-orang 'tak selaras', dimana kita bisa belajar banyak dari mereka. Ada seorang guru yang senantiasa berkata kalau dia 'melayani dengan sepenuh hati', 'membantu dengan tulus', dst. Lucunya, saya tidak pernah merasakan adanya ketulusan itu, seakan kata-kata itu dibubuhkan untuk menggiring pemikiran sang murid untuk percaya bahwa dia adalah seorang yang tulus.
Sementara sebagian besar guru saya yang lain tidak pernah menyampaikan kata sifat ini ke dalam kata-kata. Mereka membiarkan maksud dan tujuan mereka untuk sampai ke penerima lewat tindakan, getaran, energi, atau aura--bukan ucapan. Ini membuat saya memilah sosok guru ke dalam dua kategori: teori dan praktik. Saya pribadi lebih suka belajar dari guru yang walk the talk atau practice the preach (melakukan apa yang ia katakan / ajarkan) karena jelas lebih nyata dan praktis. Walau guru teoritis pun punya andil dalam memperkaya pengetahuan jiwa, guru praktikum memberi saya lebih banyak pelajaran yang telah terangkum dalam langkah-langkah mudah untuk diaplikasikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Upah Seorang Guru
Terakhir adalah imbalan; pamrih. Lalu apa imbalan yang tepat untuk guru? Saya percaya, setiap orang yang memberi dengan tulus telah mendapatkan upahnya sendiri. Semesta bekerja dengan cara yang mungkin tidak dimengerti oleh manusia, karena hukumnya selalu adil, selalu pas. Ada yang menyebutnya sebagai karma, hukum tabur-tuai, hukum kompensasi, dst. Tidak ada sesuatupun di dunia yang sia-sia; apapun yang diberi akan kembali, semua yang hilang akan diganti. Jadi ketika seseorang memutuskan menjadi guru spiritual tentu ia dengan sadar tahu bahwa imbalannya tak selalu berbentuk materi / hal duniawi.
Ada seorang guru yang marah ketika saya memutuskan untuk menyelesaikan pembelajaran padanya dan meneruskan hidup. Ia merasa telah memberi banyak (bahkan--menurutnya--semua) ilmunya pada saya dan menginginkan saya menjadi cantriknya. Normalnya mungkin orang akan menuruti kemauan guru yang seperti ini. Toh misi mulianya adalah membantu orang lain. Tapi permintaan ini terasa sangat konyol bagi saya, terlebih karena saya tidak pernah meminta pembelajaran itu, atau mengemis minta diajari secara khusus.
Saya menerima saja ketika ia berkata mau mengajari saya, toh tidak ada perjanjian yang saya tanda tangani di awal jika seusai pembelajaran saya harus mengabdi. Apalagi jika harga yang diminta oleh guru itu menyangkut hal seksual (tidak selalu seksual, tapi bisa juga bentuknya uang atau kekuasaan--ingat tiga godaan duniawi: harta, tahta, dan cinta). Langsung jelas karakter pribadi / kekeruhan jiwa guru ini di mata saya, dan seketika itu juga respek saya padanya sebagai sosok guru hilang.
Kurang ajarkah saya? Mungkin sebagian akan menilai demikian. Tapi saya yakin tugas saya bukanlah mengabdi pada satu orang. Apalagi membayar pelajaran dengan hubungan seksual, walau dalihnya adalah hubungan suci antara guru dan murid yang bisa membantu orang banyak (ya pikir logika saja di mana 'suci'-nya ya). Saya lebih suka menjalankan panggilan jiwa saya untuk mengabdi pada bangsa lewat apa yang bisa saya lakukan: tulisan dan buku.
Saya tidak punya kepentingan apapun selain untuk berbagi dan berharap bisa menginspirasi. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Tidak harus jadi bestseller karena tidak semua bisa menerima tulisan saya, dan ini wajar karena tidak semua orang suka apel. Ada yang lebih suka jeruk, pisang, atau anggur. Tapi jika ada yang mendapatkan sesuatu dari karya saya, betapa menyenangkannya!
Apa tujuan saya menulis hal ini? Saya sama sekali tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, ini untuk bahan perenungan dan pembelajaran bersama. Ironisnya pengalaman seperti ini banyak sekali dijumpai oleh para pejalan spiritual, yang akhirnya jadi trauma pada kata spiritual (walau sebenarnya dia jadi belajar banyak dari pengalaman itu). Dan saya tidak ingin ada hal serupa terjadi pada siapapun juga. Setidaknya jangan lagi ada pengalaman buruk dalam pembelajaran spiritual.
Jadi sebagaimana seorang guru bertanggung jawab menyampaikan pesan Semesta pada muridnya, saya menyampaikan pesan ini sebagai sesama murid. Anggap saja sebagai tips atau bahan pertimbangan, bukan untuk menggurui. Balik lagi: selalu tanyakan pada diri sendiri karena Guru Sejati ada di dalam dirimu sendiri.
Salam. Tabik. Namaste.
Rahayu,
_/|\_
Latihan mengenali rasa ini bisa jadi sangat menarik ketika kita bertemu dengan orang-orang 'tak selaras', dimana kita bisa belajar banyak dari mereka. Ada seorang guru yang senantiasa berkata kalau dia 'melayani dengan sepenuh hati', 'membantu dengan tulus', dst. Lucunya, saya tidak pernah merasakan adanya ketulusan itu, seakan kata-kata itu dibubuhkan untuk menggiring pemikiran sang murid untuk percaya bahwa dia adalah seorang yang tulus.
Sementara sebagian besar guru saya yang lain tidak pernah menyampaikan kata sifat ini ke dalam kata-kata. Mereka membiarkan maksud dan tujuan mereka untuk sampai ke penerima lewat tindakan, getaran, energi, atau aura--bukan ucapan. Ini membuat saya memilah sosok guru ke dalam dua kategori: teori dan praktik. Saya pribadi lebih suka belajar dari guru yang walk the talk atau practice the preach (melakukan apa yang ia katakan / ajarkan) karena jelas lebih nyata dan praktis. Walau guru teoritis pun punya andil dalam memperkaya pengetahuan jiwa, guru praktikum memberi saya lebih banyak pelajaran yang telah terangkum dalam langkah-langkah mudah untuk diaplikasikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Upah Seorang Guru
Terakhir adalah imbalan; pamrih. Lalu apa imbalan yang tepat untuk guru? Saya percaya, setiap orang yang memberi dengan tulus telah mendapatkan upahnya sendiri. Semesta bekerja dengan cara yang mungkin tidak dimengerti oleh manusia, karena hukumnya selalu adil, selalu pas. Ada yang menyebutnya sebagai karma, hukum tabur-tuai, hukum kompensasi, dst. Tidak ada sesuatupun di dunia yang sia-sia; apapun yang diberi akan kembali, semua yang hilang akan diganti. Jadi ketika seseorang memutuskan menjadi guru spiritual tentu ia dengan sadar tahu bahwa imbalannya tak selalu berbentuk materi / hal duniawi.
 |
| via lifecoachcode |
Ada seorang guru yang marah ketika saya memutuskan untuk menyelesaikan pembelajaran padanya dan meneruskan hidup. Ia merasa telah memberi banyak (bahkan--menurutnya--semua) ilmunya pada saya dan menginginkan saya menjadi cantriknya. Normalnya mungkin orang akan menuruti kemauan guru yang seperti ini. Toh misi mulianya adalah membantu orang lain. Tapi permintaan ini terasa sangat konyol bagi saya, terlebih karena saya tidak pernah meminta pembelajaran itu, atau mengemis minta diajari secara khusus.
Saya menerima saja ketika ia berkata mau mengajari saya, toh tidak ada perjanjian yang saya tanda tangani di awal jika seusai pembelajaran saya harus mengabdi. Apalagi jika harga yang diminta oleh guru itu menyangkut hal seksual (tidak selalu seksual, tapi bisa juga bentuknya uang atau kekuasaan--ingat tiga godaan duniawi: harta, tahta, dan cinta). Langsung jelas karakter pribadi / kekeruhan jiwa guru ini di mata saya, dan seketika itu juga respek saya padanya sebagai sosok guru hilang.
Kurang ajarkah saya? Mungkin sebagian akan menilai demikian. Tapi saya yakin tugas saya bukanlah mengabdi pada satu orang. Apalagi membayar pelajaran dengan hubungan seksual, walau dalihnya adalah hubungan suci antara guru dan murid yang bisa membantu orang banyak (ya pikir logika saja di mana 'suci'-nya ya). Saya lebih suka menjalankan panggilan jiwa saya untuk mengabdi pada bangsa lewat apa yang bisa saya lakukan: tulisan dan buku.
Saya tidak punya kepentingan apapun selain untuk berbagi dan berharap bisa menginspirasi. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Tidak harus jadi bestseller karena tidak semua bisa menerima tulisan saya, dan ini wajar karena tidak semua orang suka apel. Ada yang lebih suka jeruk, pisang, atau anggur. Tapi jika ada yang mendapatkan sesuatu dari karya saya, betapa menyenangkannya!
Apa tujuan saya menulis hal ini? Saya sama sekali tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun, ini untuk bahan perenungan dan pembelajaran bersama. Ironisnya pengalaman seperti ini banyak sekali dijumpai oleh para pejalan spiritual, yang akhirnya jadi trauma pada kata spiritual (walau sebenarnya dia jadi belajar banyak dari pengalaman itu). Dan saya tidak ingin ada hal serupa terjadi pada siapapun juga. Setidaknya jangan lagi ada pengalaman buruk dalam pembelajaran spiritual.
Jadi sebagaimana seorang guru bertanggung jawab menyampaikan pesan Semesta pada muridnya, saya menyampaikan pesan ini sebagai sesama murid. Anggap saja sebagai tips atau bahan pertimbangan, bukan untuk menggurui. Balik lagi: selalu tanyakan pada diri sendiri karena Guru Sejati ada di dalam dirimu sendiri.
Salam. Tabik. Namaste.
Rahayu,
_/|\_











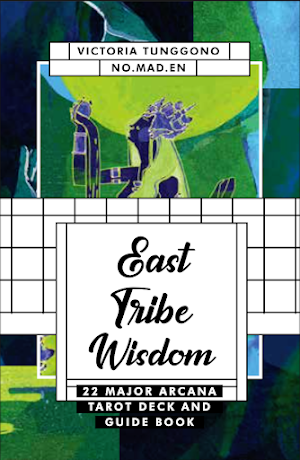









0 comments
Terima kasih sudah memberi komentar. Mohon kesabarannya menunggu saya baca dan balas komennya ya. Rahayu.